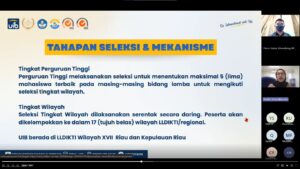Penulis: Emiliya Febriyani, S.H., M.H.
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Keluhan rakyat bertebaran, bukan hanya di jalanan, tetapi juga di ruang-ruang digital yang setiap hari kita baca. Harga-harga kebutuhan pokok naik, layanan publik sering kali mengecewakan, dan rasa keadilan seakan semakin menjauh dari jangkauan. Sementara itu, pemberitaan korupsi nyaris tak pernah absen. Dari tingkat pusat hingga daerah, dari lembaga legislatif hingga eksekutif, kita menyaksikan parade pejabat yang tak segan mengkhianati amanah rakyat. Lebih ironis lagi, sebagian dari mereka tetap tampil percaya diri, tanpa rasa malu, seolah etika, empati, dan kepedulian tak lagi relevan dalam dunia politik kita.
Bulan Agustus biasanya menjadi bulan yang penuh makna bagi bangsa ini. Upacara bendera digelar di setiap lapangan, lagu kebangsaan berkumandang, dan para pemimpin berpidato dengan segala capaian dan janji. Namun, Agustus 2025 ini memberi wajah lain, penuh paradoks, getir, bahkan berdarah.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraan di depan MPR, berbicara dengan penuh keyakinan tentang kedaulatan pangan, surplus beras, serta janji memerangi serakahnomics. Beliau menekankan bahwa bangsa akan aman jika menguasai pangan, sambil mengumumkan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bagi jutaan anak sekolah. Pidato itu sarat data, penuh capaian, dan menampilkan negara dalam posisi gagah.
Namun, hanya berselang dua pekan, jalanan Jakarta memunculkan cerita lain. Ribuan rakyat, mulai dari buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online, turun ke jalan menolak kebijakan fiskal yang dinilai memberatkan. Mereka memprotes kenaikan pajak dan iuran, sementara DPR menikamati kenaikan gaji dan tunjangan. Demonstrasi pada 28 Agustus itu berakhir tragis, seorang pengemudi ojol, Umar alias Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob.
Antara podium di Senayan dan jalan di depan gedung DPR, terlihat jurang yang lebar. Pidato berbicara tentang kejayaan, sementara rakyat kehilangan nyawa ketika menyuarakan ketidakadilan.
Pidato dan Rasa yang Hilang
Pidato kenegaraan seharusnya menjadi momen reflektif, ketika pemimpin menyapa rakyat dengan bahasa yang menyentuh hati. Namun, yang terdengar lebih sering adalah laporan panjang berupa angka, grafik, dan program. Presiden bicara tentang cadangan beras, tetapi rakyat di pasar tetap mengeluh harga sembako naik. Presiden mengklaim kesejahteraan meningkat, tetapi iuran BPJS justru makin memberatkan.

Sumber: ChatGPT
Kontras itu makin terasa ketika di bulan yang sama, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong menyampaikan Pidato National Day Rally. Ia berkata sederhana: “To keep Singapore going, we must be a we-first society.” Wong tidak menyodorkan deret angka, melainkan ajakan moral. Pemerintah, katanya, tidak hanya bekerja untuk rakyat, melainkan bersama rakyat. Ia menyebut panel warga dan forum pemuda sebagai cara melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Singkat, tetapi hangat dan mengikat. Dan bahkan di saat banyak yang mengira Singapura sudah mencapai puncaknya, PM Wong menegaskan ini baru permulaan. Dengan terus berfokus pada inovasi, teknologi dan manusia, ia yakin masa depan yang jauh lebih cerah masih ada bagi seluruh warga Singapura.
Di Indonesia, pidato terasa formal, penuh jargon birokratis, jauh dari bahasa sehari-hari rakyat. Rakyat mendengar, tetapi tidak merasa disapa. Orientasinya justru banyak ke masa lalu. Berkali-kali Presiden Prabowo menekankan soal UUD 1945 dan pemikiran dengan teori-teori ekonomi usang lain yang tidak lagi relevan. Bahkan The Economist menulis artikel berjudul “Indonesia’s New President Has Daddy Issues” (14 Agustus 2025), yang menilai Prabowo terlalu ingin mengimitasi ide-ide ayahnya, Sumitro, mulai dari koperasi hingga kebijakan fiskal. Pada bagian penutupan artikel ini justru menegaskan: “This is a travesty of Sumitros real legacy: of the disciplines fiscal policy and strong institution Indonesia badly needs?”. Pertanyaannya: apakah Indonesia sudah mencapai tahap tersebut?
Jalanan yang Bersuara
Maka, jalanan kembali mengambil peran. Pada 28 Agustus, ribuan rakyat mengepung DPR. Mereka membawa spanduk, meneriakkan tuntutan, dan berorasi lantang. Suaranya sederhana: hentikan kebijakan fiskal yang menekan rakyat kecil.
Namun, seperti yang sudah berulang kali terjadi sejak era reformasi, DPR lebih memilih diam. Gedung tinggi dengan pagar kawat berduri menjadi simbol keterpisahan antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. Polisi? Janganlah dipertanyakan. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana aparat yang lebih suka disebut “oknum”, kerap lebih sibuk melindungi elite ketimbang rakyat. Gas air mata ditembakkan, kendaraan taktis bergerak, dan dalam kekacauan itu, seorang ojol tergeletak tak bernyawa di aspal.

Sumber: ChatGPT
Umar hanyalah satu dari jutaan rakyat biasa yang saban hari berjuang di jalan. Ia tidak pernah merasakan gaji puluhan juta, tidak pernah masuk ruang rapat ber-AC, tidak punya privilese protokoler. Ia hanya mencari nafkah dengan motornya. Ironisnya, ia justru kehilangan nyawa ketika memperjuangkan keadilan yang mestinya dijamin negara.
Kematian Umar adalah simbol bahwa negara kita belum belajar menghargai suara rakyat. Demonstrasi selalu dijawab dengan gas air mata, bukan dialog. Sejak 1998 hingga kini, pola itu terus berulang, rakyat berteriak, elite menutup telinga.
Akar Masalah: Korupsi, Kejujuran dan Empati yang Hilang
Fenomena ini mengajarkan kita bahwa persoalan bangsa bukan sekadar soal kekurangan pangan atau rendahnya investasi, melainkan hilangnya kejujuran dan empati dalam politik.
Indonesia negeri kaya. Minyak, gas, batubara, nikel, emas, semua ada. Tetapi mengapa rakyat masih menjerit oleh kenaikan pajak dan iuran? Jawabannya sederhana: kebocoran akibat korupsi. Transparency International menempatkan skor korupsi kita di angka 34/100, jauh di bawah Singapura yang menempati posisi lima besar dunia.
Korupsi membuat uang rakyat bocor sebelum sampai ke sekolah, rumah sakit, dan jalan desa. Dan di tengah kebocoran itu, pejabat dan legislator tetap menikmati gaji, tunjangan, dan fasilitas tinggi. Ironis, karena di banyak negara maju, anggota parlemen bergaji moderat dan bekerja penuh sebagai pengabdian. Di Indonesia, kursi DPR masih sering dilihat sebagai jalan pintas menuju kenyamanan.

Sumber: ChatGPT
Jika Aku Menjadi Presiden
Jika aku menjadi presiden, pidato bukanlah laporan angka, melainkan janji moral. Aku ingin berkata: “Kita memang sedang kesulitan, tapi kita akan melawannya bersama.” Aku ingin memilih putra putri terbaik bangsa yang benar-benar pantas dan layak untuk bekerja. Aku ingin menerapkan efisiensi secara merata, tidak jompang apalagi membebani rakyat. Aku ingin memastikan demonstrasi tidak lagi dijawab dengan gas air mata atau rantis, melainkan dengan dialog terbuka.
Presiden tidak hanya berbicara menggelegar di podium, tetapi hadir di ruang-ruang sempit penderitaan rakyat. Aku ingin seperti Umar bin Khattan r.a., seorang pemimpin yang berjalan di malam hari untuk memastikan tidak ada lagi seorang ibu yang “memasak batu” demi menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Presiden bukan simbol kekuatan negara, melainkan cermin harapan rakyat.
Agustus ini telah memperlihatkan dua wajah negeri, pidato panjang di gedung megah, dan jerit rakyat di jalanan. Sayangnya, antara keduanya tidak pernah bertemu.
Jika aku menjadi presiden, aku ingin dikenang bukan karena pidato membara berjam-jam, tetapi karena keberanian menghapus jarak antara podium dan jalanan. Karena kemerdekaan sejati bukanlah parade di istana, melainkan kebahagiaan sederhana: rakyat bisa hidup tanpa takut, tanpa terbebani, dan tanpa kehilangan nyawa di jalan ketika bersuara.
Editor: Ambarwulan, S.T.
Referensi
- Sekretariat Kabinet RI-Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Pangan Sebagai Pilar Utama (15 Agustus 2025), diakses: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tegaskan-kedaulatan-pangan-sebagai-pilar-utama-ketahanan-nasional/
- Tempo-Kronologi Mobil Brimob Lindas Pengemudi Ojol saat Demo DPR (29 Agustus 2025), diakses: https://www.tempo.co/politik/kronologi-mobil-brimob-lindas-pengemudi-ojol-hingga-tewas-saat-demo-di-dpr-2064223
- Channel News Asia (CNA)-NDR 2025: Lawrence Wong on Building a We-First Society (9 Agustus 2025), diakses: https://www.channelnewsasia.com/singapore/ndr-lawrence-wong-society-collective-action-singapore-spirit-5298826
- The Economist-Indonesia’s New President Has Daddy Issues (14 Agustus 2025), diakses: https://www.economist.com/asia/2025/08/14/indonesias-new-president-has-daddy-issues
- Transparency International-Corruption Perceptions Index 2024, diakses: https://www.transparency.org/en/cpi/2024