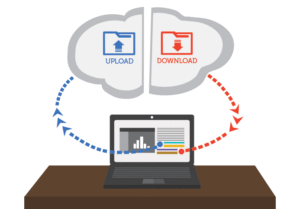Penulis: Ritki Wijaya (2451133)

Sumber: ChatGPT
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai ketentuan di dalamnya menimbulkan perdebatan publik. Salah satu pasal yang paling banyak disorot ialah Pasal 240 KUHP, yang mengatur tindakan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina pemerintah atau lembaga negara dapat dipidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau dikenakan denda kategori II (News, 2022). Sekilas, aturan ini tampak bertujuan menjaga martabat dan wibawa lembaga negara. Namun demikian, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut justru berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan terhadap pasal ini menjadi penting agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi warga negara.
Dalam negara hukum yang demokratis, pemerintah sejatinya bukanlah entitas yang kebal terhadap kritik dari masyarakat. Justru, lembaga publik perlu terbuka terhadap pengawasan rakyat agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Pasal 240 KUHP berpotensi menghidupkan kembali pasal-pasal karet warisan kolonial yang dulunya digunakan untuk membungkam kritik terhadap penguasa (Times, 2022). Menurutnya, ukuran kehormatan pemerintah tidak diukur dari sedikitnya kritik, melainkan dari kemampuannya menanggapi kritik tanpa melakukan kriminalisasi (Times, 2022). Dengan demikian, penghormatan terhadap lembaga negara seharusnya dibangun melalui integritas dan keterbukaan, bukan melalui rasa takut terhadap hukum.
Lebih lanjut, permasalahan mendasar dari Pasal 240 KUHP terletak pada sifatnya yang lentur dan multitafsir, terutama dalam menentukan unsur “penghinaan.” Ketidakjelasan batas antara kritik yang sah dan penghinaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dalam praktiknya, tafsir yang subjektif dari aparat penegak hukum berpotensi membuka ruang penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu. Sebagai pembanding, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 pernah membatalkan pasal serupa dalam KUHP lama melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Mahkamah Konstitusi, 2006). MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa dimasukkannya kembali ketentuan serupa dalam KUHP baru menandai kemunduran dalam reformasi hukum nasional (Ellandra et al., 2022).
Meskipun pemerintah beralasan bahwa Pasal 240 merupakan delik aduan yang berarti hanya dapat diproses jika lembaga yang merasa dihina melapor namun kekhawatiran publik tetap tidak dapat diabaikan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menilai bahwa keberadaan pasal ini berpotensi menimbulkan efek gentar (chilling effect) di kalangan masyarakat (Masyakarat, 2023). Akibatnya, banyak orang memilih diam daripada menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik karena takut dikriminalisasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko mengikis daya kritis dan melemahkan partisipasi warga dalam kehidupan demokratis. Padahal, negara hukum yang sehat membutuhkan masyarakat yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme penerapan pasal ini perlu diawasi agar tidak melanggar prinsip kebebasan sipil yang dijamin konstitusi.
Lebih jauh lagi, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk melindungi hak berekspresi setiap warga negara. Komite Hak Asasi Manusia PBB (Human Rights Committee) dalam General Comment No. 34 menegaskan bahwa pejabat publik harus lebih terbuka terhadap kritik karena mereka bekerja atas mandat rakyat (UNHRC, 2011). Oleh sebab itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, sesuai dengan prinsip negara demokratis. Dalam konteks ini, Pasal 240 KUHP dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak disertai pedoman penerapan yang jelas dan transparan. Akibatnya, ruang publik bisa berubah menjadi area yang membatasi keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat (Online, 2023).
Dari sisi hukum pidana, delik penghinaan seharusnya memiliki batasan yang objektif dan dapat diukur dengan jelas. Penghinaan yang benar-benar bersifat fitnah atau menyerang kehormatan pribadi berbeda dengan kritik yang didasarkan pada kepentingan publik. Jika unsur “penghinaan” tidak dirumuskan dengan tegas, maka aparat penegak hukum dapat menilai kritik kebijakan sebagai tindak pidana. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan asas lex certa, yang menuntut kejelasan rumusan hukum pidana agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Hukum yang kabur hanya akan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan menghambat diskursus publik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang serta aparat penegak hukum perlu berhati-hati dalam menafsirkan pasal ini agar tidak mengikis nilai-nilai demokrasi.
Dalam konteks sosial-politik, kehadiran Pasal 240 KUHP mencerminkan adanya tarik-menarik antara keinginan menjaga stabilitas pemerintahan dan semangat kebebasan berekspresi. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan ini diperlukan untuk melindungi kehormatan lembaga negara dari tindakan yang merendahkan martabatnya (Republik.id, 2022). Namun, batas antara ujaran kebencian dan kritik terhadap kebijakan publik sering kali sangat tipis dan mudah disalahartikan. Tanpa pedoman yang tegas, pasal ini berpotensi digunakan untuk membatasi ruang gerak kelompok atau individu yang kritis terhadap kekuasaan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tengah membangun kembali dinding pembatas terhadap kebebasan sipil. Padahal, dalam sistem hukum demokratis, perbedaan pendapat justru merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dijamin keberadaannya.
Pada akhirnya, Pasal 240 KUHP sebenarnya dapat membawa dampak positif apabila diterapkan secara bijak dan berkeadilan. Ketentuan ini dapat digunakan untuk menindak tindakan yang secara nyata bermaksud menghina lembaga negara secara tidak berdasar. Namun, penerapan yang tidak cermat justru dapat menimbulkan ketakutan kolektif dan menutup ruang dialog publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan pasal ini tidak memiliki muatan politik dan didasarkan pada bukti yang objektif. Selain itu, pendidikan hukum bagi masyarakat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan batas antara kritik dan penghinaan. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran publik, bukan sebagai alat pembatas kebebasan (Ellandra et al., 2022).
Sebagai penutup, keberadaan Pasal 240 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dipandang secara proporsional, yakni antara menjaga kehormatan lembaga negara dan melindungi kebebasan rakyat. Pasal ini dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi menjaga wibawa lembaga negara, namun di sisi lain dapat membatasi kebebasan sipil apabila diterapkan tanpa pengawasan. Pemerintah yang kuat seharusnya tidak merasa terancam oleh kritik, melainkan menjadikannya sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Negara hukum sejati bukanlah yang menakuti rakyat dengan ancaman pidana, melainkan yang membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Kritik bukanlah bentuk penghinaan, tetapi tanda cinta terhadap bangsa dan dorongan untuk memperbaiki pemerintahan. Karena itu, menjaga keseimbangan antara wibawa negara dan kebebasan rakyat merupakan kunci keberlangsungan demokrasi Indonesia.
Editor: Ambarwulan, S.T.
Referensi
- Ellandra, A. Z., Faqih, M., & Azizi, K. (2022). Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). Journal of Studia Legalia, 3(01), 1–12. https://doi.org/10.61084/JSL.V3I01.20
- Mahkamah Konstitusi. (2006). Putusan Nomor 140/PUU-VII/2006. MKRI.
- Masyakarat, L. B. H. (2023). Pembatasan oleh Negara yang Melampaui Batas: Legal Opinion tentang Hak Kebebasan Berpendapat dalam KUHP. LBH Masyarakat.
- News, B. (2022). DPR sahkan kitab hukum pidana baru yang dikritik mengancam kebebasan – BenarNews Indonesia. https://www.benarnews.org/indonesian/berita/dpr-sahkan-kuhp-bermasalah-12062022114002.html?
- Online, H. (2023). MK Diminta Batalkan Pasal Penghinaan Presiden-Lembaga Negara dalam KUHP Baru. Hukum Onlice.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-diminta-batalkan-pasal-penghinaan-presiden-lembaga-negara-dalam-kuhp-baru-lt63d3563c8cb8d/?
- Republik.id. (2022). RKUHP Resmi Jadi UU. Republik. https://www.republika.id/posts/35157/rkuhp-resmi-jadi-uu?
- Times, I. (2022). [WANSUS] Pakar Hukum Bivitri Susanti: Kupas RKUHP | IDN Times. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/wansus-pakar-hukum-bivitri-susanti-kupas-kontroversial-isi-rkuhp-00-sbfjr-r4v830
- UNHRC. (2011). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Human Right Committe. https://doi.org/10.5771/9783748929833-209-1