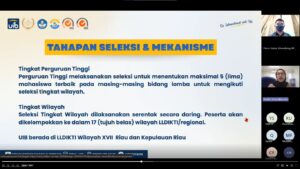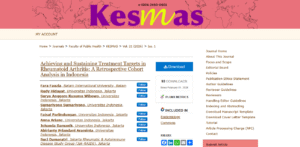Penulis: Dr. Rufinus H. Hutauruk, S.H., M.M., M.H.
Kejahatan Korporasi dan Tantangan Global
Globalisasi ekonomi dan liberalisasi pasar bukan hanya membuka ruang bagi pertumbuhan bisnis, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di sektor ekonomi. Fenomena ini telah diakui sejak Kongres PBB 1985 di Jenewa, yang menyoroti peningkatan signifikan tindak pidana ekonomi seperti penggelapan pajak, penyelundupan, penipuan asuransi, dan praktik suap yang dilakukan oleh badan usaha dengan kedok kegiatan ekonomi yang sah.
Sosiolog Sally S. Simpson mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai perilaku badan hukum atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi dan dilarang oleh undang-undang. Tujuannya beragam — memperoleh keuntungan finansial, menghindari kerugian, atau mencari keunggulan bisnis — namun semuanya berakar pada penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.
Kasus-kasus besar seperti suap American Motor Corporation (1982) menunjukkan bahaya kejahatan korporasi terhadap keselamatan publik. Di Amerika Serikat, kerugian akibat pelanggaran korporasi diperkirakan mencapai US$200 miliar per tahun, dua puluh kali lipat lebih besar daripada kejahatan konvensional. Untuk menanggulanginya, pemerintah AS membentuk Corporate Fraud Task Force (2002) dan menerapkan False Claims Act, yang memberi insentif finansial bagi warga yang melaporkan penipuan korporasi.
Sistem Hukum dan Latar Belakang Indonesia
Sistem hukum Indonesia termasuk dalam tradisi Romano-Germanic (Civil Law) karena pengaruh kolonial Belanda, namun unsur hukum Islam dan hukum adat tetap hidup berdampingan, menjadikannya sistem campuran yang unik. Dalam kerangka Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum — tiga elemen yang harus berjalan serasi untuk menjamin keadilan dan kepastian.
Dalam hukum pidana, dikenal hukum pidana materiil (mengatur perbuatan yang dapat dihukum) dan hukum pidana formil (mengatur proses peradilan pidana). Prinsip dasar yang menjadi fondasinya adalah asas legalitas — tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar undang-undang (nullum crimen, nulla poena sine lege).
Sistem hukum pidana Indonesia dikodifikasi dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958) dan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Namun, perkembangan teknologi dan ekonomi memunculkan berbagai undang-undang khusus di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955, UU Perbankan, UU Pencucian Uang, UU Terorisme, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa hukum pidana terus beradaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi.
Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana
Awalnya, adagium klasik societas delinquere non potest — “korporasi tidak dapat melakukan kejahatan” — mendominasi karena badan hukum dianggap tidak memiliki niat jahat (mens rea) dan tubuh fisik. Namun, doktrin ini mulai ditinggalkan seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam perekonomian.
Dalam praktik internasional, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah berlangsung lama: di Amerika Serikat melalui kasus New York Central & Hudson River R.R. vs United States (1909), dan di Belanda sejak Wet op de Economische Delicten (1950).
Indonesia mulai mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana sejak UU Darurat 1951 dan terutama UU No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Saat ini, puluhan undang-undang mengatur bahwa korporasi dapat dituntut dan dipidana, baik bersama pengurusnya maupun secara mandiri. Misalnya, dalam UU Perikanan 2004, UU Perlindungan Konsumen 1999, dan UU Pemberantasan Korupsi 1999 jo. 2001.
Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pertanggungjawaban pidana merupakan proses pemberian celaan hukum kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat dipidana. Dalam konteks korporasi, berbagai teori menjelaskan dasar pertanggungjawaban ini:
- Teori Identifikasi (Identification Theory)
Menganggap pikiran dan kehendak para pengendali (direksi, manajer senior) sebagai pikiran dan kehendak korporasi itu sendiri. Jika tindakan dilakukan dalam lingkup kewenangan mereka, maka unsur mens rea korporasi dianggap terpenuhi. - Teori Vicarious Liability
Dikenal juga sebagai respondeat superior, menempatkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya sepanjang dilakukan dalam hubungan kerja. - Teori Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak)
Meniadakan keharusan membuktikan unsur kesalahan. Prinsip ini digunakan untuk pelanggaran yang mengancam keselamatan publik, lingkungan, atau kepentingan sosial, di mana pembuktian mens rea sulit dilakukan.
Dalam RKUHP 2004 Pasal 35 ayat (2) ditegaskan, seseorang — termasuk badan hukum — dapat dipidana semata-mata karena telah memenuhi unsur tindak pidana tanpa memperhatikan kesalahan. Artinya, korporasi dapat dikenai pidana walau niat jahat tidak terbukti, sepanjang pelanggaran hukum terjadi secara faktual.
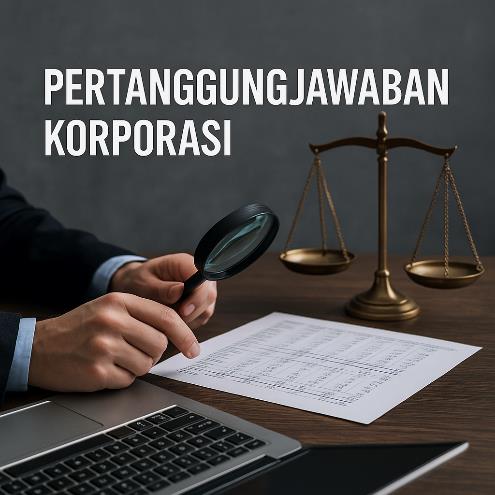
Sumber: ChatGPT
Pidana dan Pemidanaan terhadap Korporasi
Pemidanaan terhadap korporasi harus memperhatikan asas legalitas dan proporsionalitas. Tujuannya tidak sekadar menghukum, melainkan juga menegakkan keadilan, mencegah pengulangan, dan memulihkan kerugian publik.
Ahli hukum Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager menawarkan sejumlah kriteria untuk menentukan sanksi, antara lain: derajat kerugian publik, tingkat keterlibatan manajer, frekuensi pelanggaran, bukti niat, riwayat pelanggaran, dan tingkat kerja sama korporasi dalam proses hukum.
Sanksi terhadap korporasi di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan perampasan seluruh atau sebagian usaha korporasi. Namun, penerapan sanksi berat seperti pembubaran harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena dapat berdampak pada pekerja, pemasok, dan masyarakat luas.
Selain pidana denda, beberapa bentuk pemidanaan alternatif yang relevan untuk korporasi antara lain:
- Hukuman Percobaan (Probation) – pengawasan hukum dengan kewajiban menjalankan program good corporate governance;
- Denda Saham (Equity Fine) – penyerahan sebagian saham kepada pemerintah;
- Hukuman Pelayanan Masyarakat (Community Service) – misalnya kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan;
- Pencabutan Izin Usaha atau Pembekuan Kegiatan;
- Pembubaran Korporasi atau Perampasan Aset bila pelanggaran sangat berat.
Pendekatan ini sejalan dengan teori deterrence, yang menekankan efek jera melalui ancaman terhadap reputasi dan keberlangsungan bisnis korporasi.
Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai Mekanisme Pencegahan
Dalam era keterbukaan ekonomi dan regulasi Environmental, Social, and Governance (ESG), pencegahan lebih penting daripada sekadar penghukuman. Oleh karena itu, uji tuntas hukum dan keuangan (legal & financial due diligence) menjadi instrumen penting untuk menilai kepatuhan dan integritas korporasi sebelum melakukan aksi bisnis.
Konsep ini diatur dalam UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan POJK 66/POJK.04/2017, yang mewajibkan setiap emiten dan konsultan hukum memastikan seluruh dokumen publik akurat dan transparan. Dengan uji tuntas, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi lebih awal, dan korporasi terdorong menjunjung prinsip kehati-hatian serta profesionalisme dalam kegiatan usahanya.
Penutup
Korporasi kini diakui bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi juga subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan pidana. Sistem hukum pidana Indonesia terus berkembang dari paradigma lama — yang menolak konsep “korporasi dapat bersalah” — menuju paradigma baru yang menempatkan badan hukum sebagai aktor penting dalam penegakan keadilan dan tata kelola ekonomi berkelanjutan.
Penerapan teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability menjadi fondasi untuk menegakkan prinsip rule of law dalam dunia usaha. Namun, pemidanaan terhadap korporasi harus tetap memperhatikan keseimbangan antara efek jera, pemulihan kerugian publik, dan keberlangsungan ekonomi nasional.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya soal hukuman, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam sistem hukum Indonesia yang beradab.
Editor: Ambarwulan, S.T.
Referensi
- Sally S. Simpson, Corporate Crime and Regulation, Oxford University Press, 2010.
- Muladi, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Genta Press, 2013.
- Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager, Corporate Crime, Free Press, 1980.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- POJK No. 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum Pasar Modal